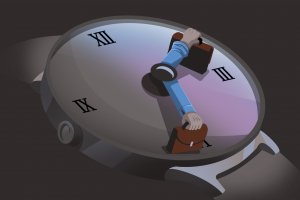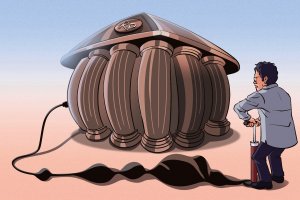Varian baru Delta menjadi kambing hitam lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca-libur Hari Raya Idul Fitri. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat varian virus yang berasal dari India tersebut telah masuk ke beberapa daerah, salah satunya di Jawa Tengah. Di provinsi itu, jumlah kasus meroket hingga 368% hanya dua pekan setelah lebaran.
Ledakan kasus positif dan kematian akibat Covid-19 pun terus menjalar. Secara nasional, angkanya terus menanjak yang pada Minggu, 4 Juli 2021 tercatat sebesar 27.233 kasus dan merenggut 555 jiwa dalam sehari. Pemerintah mengakui gagal memprediksi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Idul Fitri.
“Karena jujur, kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid ini, dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa,” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Kamis 1 Juli 2021.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat ada 11 varian baru virus corona yang bermutasi dari virus aslinya. Empat di antaranya diketahui telah terdeteksi di tanah air, seperti varian Delta (B.1.617.2) yang daya menularnya 97% lebih tinggi. Selain itu, varian Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), dan Kappa (B.1.617.1) juga mulai menjangkit.
Para ilmuwan memperkirakan varian baru tersebut memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dari varian asli yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan penelitian Finlay Campbell, Brett Archer, Henry Laurenson-Schafer, dkk, tingkat penularannya yang cepat sehingga perlu menjadi perhatian (Variant of Concern/VoC) dan diawasi (Variant of Interest/VoI).
“Selain menunjukkan gejala dan daya transmisi yang lebih cepat, varian baru ini juga dapat ‘melarikan diri’ dari antibodi yang terbentuk dari vaksin,” kata epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani kepada Katadata.co.id, Jumat 2 Juli 2021.
Namun, Laura mengingatkan sebaiknya pemerintah tidak buru-buru menyimpulkan bahwa varian Delta yang menjadi biang kerok lonjakan kasus Covid-19. Persoalannya belum ada testing nasional yang masif untuk membuktikan lonjakan kasus pasca-lebaran berasal dari varian Delta seperti di India.
“Kalau di Kudus dan Bangkalan memang karena tiba-tiba kasusnya naik tinggi. Jadi pemerintah akhirnya testing dan menganalisis penyebabnya, sehingga ketahuan ada varian Delta di wilayah tersebut,” ujarnya.
Laura mencontohkan, India dan Inggris dapat mendiagnosa penyebab kenaikan kasus aktif Covid-19 setelah men-testing dan men-tracing 70% persen dari populasinya. Sementara, testing rate Covid-19 di Indonesia masih jauh dari harapan. “Kalau bisa sehari ada sejuta orang Indonesia yang di-testing.”
Mengapa Testing Covid-19 di Indonesia Masih Rendah?
Rendahnya tingkat pengujian sampel Covid-19 ini menyebabkan para epidemiolog sulit mempercayai data pemerintah. Mereka menilai jumlah kasus yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi riil. “Menurut kami (jumlah kasus) akan lebih banyak apalagi tracing belum maksimal seperti standar WHO,” ujar Laura.
Our World in Data, sebuah proyek penelitian nirlaba yang berbasis di University of Oxford, mencatat angka testing Covid-19 Indonesia termasuk terendah di Asia. Hingga 30 Juni, rasio tes Indonesia rata-rata hanya 0,3 per 1.000 populasi atau 300 orang yang dites dari sejuta penduduk dalam sehari.
Indikator kasus riil yang lebih besar berikutnya terlihat dari naiknya angka kepositifan atau rasio positif. Hal ini, kata Laura, disebabkan tes Covid-19 yang rendah turut berdampak pada rasio positif Covid-19 di tanah air.
Sejak 13 Juni 2021, tingkat kepositifan (positivity rate) harian Indonesia mencapai 20,4%. Angkanya terus berfluktuasi seiring dengan cakupan tes yang juga naik-turun. Puncaknya pada 28 Juni 2021 dengan 70.308 orang dites dengan tingkat kepositifan mencapai 29,43%.
Sehari setelahnya, tingkat kepositifan menyusut jadi 18,07% namun dengan jangkauan tes yang lebih masif hingga 113.265 orang dalam sehari. Kondisi ini menggambarkan, bahwa jangkauan tes yang luas dapat menekan tingkat kepositifan. Tingkat kepositifan adalah persentase dari jumlah kasus baru dibagi dengan jumlah tes orang yang dites dalam satu hari.
Jadi dengan jumlah testing yang tinggi, meski jumlah kasus Covid-19 semakin banyak tapi dapat memberi peringatan kepada semua pihak. Terutama laju penularan penyakit di dalam suatu populasi. Hal ini lantaran sumber penularan, termasuk seseorang yang tak bergejala pun dapat segera teridentifikasi.
Indonesia pernah memenuhi standar rasio positif standar 5% yang ditetapkan WHO pada akhir Mei hingga awal Juli 2020. Pada waktu itu pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah, sehingga rasionya dapat ditekan hingga di bawah 5%. Ironisnya, sejak itu tingkat kepositifan terus melampaui batas WHO, bahkan angkanya makin menjauhi standar yang ditetapkan.
Laura mengatakan, tingkat kepositifan yang tinggi sebagai tanda pemerintah belum mengandalkan tes dan pelacakan kontak erat secara optimal. Menurutnya, hal ini sangat berbahaya lantaran menyebabkan risiko penularan yang lebih besar di masyarakat.
“Rata-rata di Indonesia kan yang dites orang dengan gejala, sedangkan yang tidak bergejala tidak tes. Ini yang berbahaya kalau ternyata yang tidak bergejala ini positif Covid-19 dan bebas beraktivitas, sehingga menularkan ke orang banyak,” ujarnya.
Persoalannya lagi rasio lacak-isolasi (RLI) atau tracing Indonesia masih jauh dari standar. Idealnya, rasio 1:30 yang artinya setiap kasus positif dapat terlacak 30 orang lainnya.
Berdasarkan data KawalCovid19, RLI Indonesia hanya sebesar 1,01 poin. Artinya hanya satu orang terlacak dari tiap kasus yang terkonfirmasi. RLI tertinggi di tanah air ada di Kalimantan Timur. Itu pun hanya sebesar 2,84 poin, yakni hanya tiga orang tiap kasus terkonfirmasi. Di DKI Jakarta yang memiliki kasus terbanyak, RLI hanya sebesar 2,27 poin.
Sementara banyak provinsi lain yang RLI-nya tak mencapai satu poin. Di Bali, Sumatera Utara, dan Papua Barat bahkan tercatat nol poin. Hal ini menggambarkan tak ada kontak erat dari tiap kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Permasalahan yang Menghambat Testing
Pada awal pandemi, Presiden Joko Widodo sempat memuji Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu provinsi dengan penanganan Covid-19 terbaik. Cara manjur yang dilakukan Sumbar kala itu adalah dengan memasifkan tes dan kontak erat yang baik, sehingga bisa menekan rasio positif.
Andani Eka Putra adalah orang di balik keberhasilan tes Covid-19 di Sumbar. Saat ini, pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tersebut diminta menjadi tenaga ahli di Kemenkes dalam penanganan pandemi Covid-19.
Menurut dia, salah satu keberhasilan Sumbar pada waktu itu adalah dengan melakukan kolaborasi di antara jaringan laboratorium yang ada di sana. Laboratorium-laboratorium tersebut berada di bawah satu komando sehingga memudahkan koordinasi.
Begitu pun dalam pengadaan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan tes merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Hasilnya, kata dia, kapasitas tes meningkat dari 200 sampel menjadi 3.500 sampel per hari.
“Dulu kami mulai testing Mei 2020. Kami periksa Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, dan Jambi. Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari rasio positif, rasio testing, dan rasio kontak erat,” ujar Andani kepada Katadata.co.id.
Namun keberhasilan di Sumbar sulit dibawa ke skala nasional. Andani mengakui jumlah tes Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka cukup dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Seharusnya, tes rata-rata harian di Indonesia sebesar 500 ribu per hari, sehingga dalam sepekan ada 3,5 juta orang yang dites.
Nyatanya jumlah pemeriksaan Indonesia dalam kurun waktu sepekan, yakni pada 21-27 Juni 2021 hanya 570.438 sampel. Jumlah tes tertinggi ada di Jakarta sebanyak 165.486 sampel dan terendah di Sulawesi Barat hanya 335 sampel.
“Sebagai ilustrasi di India, mereka lakukan tes kepada 2,5-3,5 juta orang sehari. Kalau kita penduduknya 1/5 dari India ya idealnya paling tidak 500-600 ribu setiap hari. Nyatanya Indonesia baru 500 ribu per minggu,” katanya.
Cara mengukur seberapa banyak jumlah penduduk yang harus dites, menurut Andani, dilihat dari angka rasio positif. Jika rasio positif di bawah 5% berarti testing standarnya 1 per 1.000 penduduk per pekan. Jika rasio positif lebih tinggi, berarti orang yang dites harus dinaikkan sampai jumlah yang optimal.
Andani mengakui ada sederet problem yang menjadi batu sandungan testing, tracing, dan treatment di tanah air. Pertama, adalah kondisi laboratorium di berbagai daerah yang terpisah-pisah dengan kapasitas yang terbatas. Dia mengungkapkan kapasitas tes rata-rata laboratorium di Indonesia hanya 50 sampai 100 orang per hari.
“Saya tidak yakin kita bisa meniru India, tapi separuhnya saja sudah hebat. Karena rasio di Indonesia saat ini sekitar 3 per 1.000 penduduk per minggu. Itupun sudah campur antara antigen dan PCR,” kata Andani.
Kedua, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah (pemda) untuk menyuplai bahan kebutuhan tes. Di samping itu, dia mengatakan, penanganan pandemi di Indonesia masih berbasis pada jumlah kasus. Akibatnya ada pemda yang takut masuk kategori zona merah dan harus memberlakukan pembatasan wilayah.
Lebih lanjut Andani menyampaikan, idealnya penambahan kasus positif di Indonesia sebesar 60 ribuan per hari. Hal ini dinilainya akan memudahkan tindakan pelacakan kontak erat.
“Penambahan jumlah kasus positif kita kan tertinggi baru sekitar 20 ribuan, berarti testing-nya masih rendah. Kalau yang di-testing banyak, kita jadi tahu sumber virusnya. Kalau kita nggak tahu, pandemi Covid-19 nggak selesai-selesai,” ujarnya.
Persoalan lainnya adalah Indonesia masih ketergantungan impor bahan dan alat tes. Sementara India bisa memproduksi sendiri bahan alat kesehatan seperti tes Covid-19 dan vaksin.
Selain berbagai kendala tersebut, tingkat akurasi tes dan biaya tes juga menjadi persoalan. Masyarakat banyak yang kebingungan dengan tingkat akurasi tes cepat dan antigen. Sementara para ahli lebih menyarankan tes PCR karena bisa mendeteksi materi genetik dari virus, sehingga lebih akurat.
Namun dengan harga tes PCR antara Rp 800 ribu hingga Rp 2,5 juta dinilai mahal bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Sampai saat ini pemerintah belum memberikan insentif untuk meringankan biaya PCR bagi masyarakat.
Pentingnya Testing, Tracing, dan Treatment
Andani menjelaskan testing, tracing, dan treatment sangat penting untuk dua hal, yakni diagnosis penyebab virus dan memutus mata rantai penularan virus. Dengan pengujian yang masif, para peneliti dapat menganalisis virus penyebab kasus. Sementara dengan melacak kontak erat dan vaksinasi bisa membantu meredam penularan virus.
Saat ini pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Maka pada periode inilah, pentingnya meningkatkan tes, lacak kontak erat, dan perawatan Covid-19.
“PPKM darurat bisa optimal kalau testing, tracing, dan kepatuhan prokes dilakukan. Kalau lihat India, dalam tiga bulan bisa turunkan kasus,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Laura. Menurutnya, kurva kasus Covid-19 di Indonesia dapat mencapai puncaknya dan mulai mendatar jika tes Covid-19 ditingkatkan dalam jumlah besar. Dengan demikian tingkat positivitasnya bisa turun di bawah 5 persen dan masyarakat tetap menjalankan prokes sebagai kewajibannya.
“Lebih baik pemda-pemda transparan dengan angka kasusnya, supaya bisa dianalisis penyebabnya. Pemerintah pun bisa membuat kebijakan menanggulangi Covid-19 yang lebih on target dan efektif,” katanya.
Editor: Aria W. Yudhistira