Job Fair yang Tidak Fair
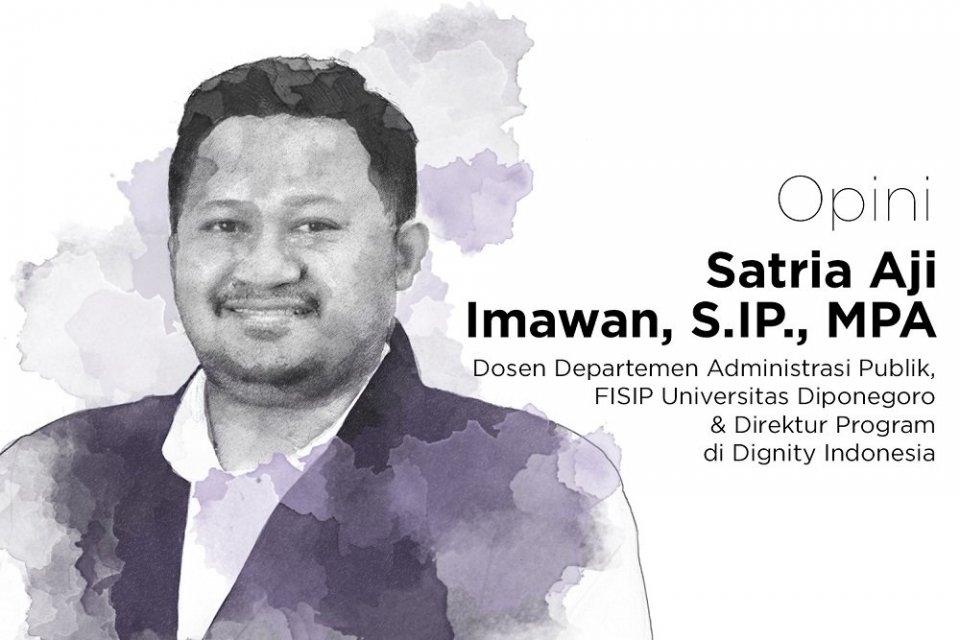
Beberapa waktu terakhir, viral di media sosial video yang menampilkan antrean para pencari kerja yang membludak di acara job fair. Ribuan orang berdesakan memadati area job fair dan rela menunggu berjam-jam demi memperoleh pekerjaan.
Pemandangan ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, menunjukkan semangat anak muda di dalam mencari pekerjaan. Namun di sisi lain, ada bara realitas yang lebih kompleks di dalam menyoroti krisis ketenagakerjaan yang menghantui kita.
Sebenarnya, fenomena job fair yang dipadati lautan manusia bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, kita menyaksikan pola yang sama. Namun, yang menarik, setiap kali peristiwa ini muncul ke permukaan, diskusi publik sering hanya berhenti pada aspek permukaan, yaitu bagaimana pengelola acara memperbaiki manajemen antrean, bagaimana peserta mempersiapkan CV, atau bagaimana perusahaan menarik calon pekerja.
Diskursus jarang menyentuh pertanyaan fundamental seperti mengapa job fair selalu dipadati pencari kerja dalam jumlah besar? Pesan apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan secara nasional?
Setiap tahun, Indonesia melahirkan jutaan lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32% atau sekitar 7,2 juta orang.
Sebagian besar penganggur ini berasal dari kelompok usia produktif, yakni 15-24 tahun. Angka ini belum termasuk angka underemployment (bekerja di bawah jam kerja layak) sebesar 8% dan informal employment yang menyentuh 58–59%. Angka-angka ini menunjukkan dominasi TPT, bekerja di bawah jam kerja layak, dan pekerjaan tidak tetap masih mewarnai struktur ketenagakerjaan nasional.
Penjelasan data-data tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dengan pertumbuhan angkatan kerja. Misalnya, industri manufaktur yang dulu menjadi andalan penyerapan tenaga kerja kini menghadapi tekanan globalisasi, otomatisasi, dan relokasi pabrik ke negara-negara berbiaya produksi lebih murah.
Pada saat yang sama, sektor jasa yang berbasis teknologi dan industri kreatif belum mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar karena membutuhkan keterampilan khusus.
Hal-hal inilah yang menjelaskan mengapa job fair selalu digandrungi publik. Job fair menyimpan harapan para pencari kerja untuk melakukan komunikasi door-to-door dengan perusahaan sehingga dapat memiliki kesempatan wawancara cepat serta memperoleh pekerjaan tetap.
Namun di tengah disparitas antara kemampuan dan peluang, opportunity tersebut tidak tersedia bagi semua orang. Hal ini terjadi karena tantangan ketenagakerjaan Indonesia secara kontemporer.
Ketidaksesuaian keterampilan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja semakin tinggi. Banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki ijazah, tetapi tidak dibekali dengan keterampilan praktis yang relevan dengan industri. Sebaliknya, banyak perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.
Riset World Bank (2023) menunjukkan, lebih dari 50% pengusaha di Indonesia mengaku mengalami kesulitan mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Temuan ini memperlihatkan adanya indikasi atas kurikulum pendidikan yang masih terlalu berorientasi pada penguasaan teori, kurangnya pembelajaran berbasis praktik, serta minimnya link and match antara institusi pendidikan dan dunia industri.
Job fair kemudian menjadi semacam pasar besar bagi perusahaan mencoba menjaring kandidat dengan cepat. Kebutuhan cepat ini direspon dengan para pencari kerja yang berbondong-bondong menyerahkan Curriculum Vitae (CV) dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Namun kemudian sebagian besar harapan itu berujung pada kekecewaan karena adanya gap keterampilan dan kebutuhan.
Dengan fenomena seperti ini, kita harus mengubah job fair sebagai solusi holistik. Tentu saja, job fair tentu bukan jawaban bagi problem struktural ketenagakerjaan kita karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tapi setidaknya, ratusan ribu orang memiliki kesempatan yang fair di dalam mencari peluang kerja. Keadilan tersebut dapat diperoleh dengan pembuatan sistem job fair yang yang berkualitas dan sistemik.
Job fair idealnya dilengkapi dengan sesi pelatihan keterampilan kerja, career coaching, simulasi wawancara, bahkan asesmen keterampilan digital sebagai penunjang. Sayangnya, banyak job fair yang justru lebih menyerupai pasar CV massal yang memperlihatkan banyak perusahaan hanya sekadar mengumpulkan data pelamar tanpa komitmen serius untuk merekrut secara langsung.
Fenomena seperti ini secara lebih luas dapat memunculkan kecemasan kolektif di kalangan lulusan baru. Para pencari kerja dapat memiliki perasaan bersaing dalam kompetisi yang tidak seimbang antara posisi yang tersedia dengan jumlah pelamar.
Perasaan tidak percaya diri ini dapat membuka celah untuk praktik tidak sehat seperti calo kerja, pungutan liar, hingga penipuan lowongan kerja yang mengeksploitasi harapan pencari kerja. Apabila ini tidak dicegah, rasa frustrasi dalam mencari pekerjaan formal dapat berdampak kepada terserapnya para pencari kerja pada pekerjaan-pekerjaan informal yang rentan dan tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Tentu uraian-uraian di atas harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk menemukan solusi antisipatif dan integratif. Masalah-masalah ketenagakerjaan bukan hanya urusan Kementerian Ketenagakerjaan, namun juga menyangkut sektor pendidikan, industri, investasi, hingga reformasi birokrasi.
Sebagai contoh, dunia pendidikan harus melakukan reformasi kurikulum secara menyeluruh untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja masa kini dan masa depan. Pendidikan vokasi dan upskilling pekerja muda perlu menjadi prioritas bagi pemerintah. Apalagi saat ini teknologi informasi menjadi skills wajib yang perlu dimiliki oleh para pencari kerja.
Langkah lainnya adalah pemerintah harus menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif dan sehat, yang mampu mendorong lahirnya industri padat karya modern di berbagai daerah. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita hanya dinikmati oleh sektor-sektor padat modal yang minim penciptaan lapangan kerja.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penguatan sistem informasi pasar kerja berbasis data yang akurat. Dengan begitu, pencari kerja bisa mengakses informasi peluang kerja secara lebih transparan dan perusahaan pun dapat menemukan kandidat yang tepat secara lebih efisien, tanpa harus mengandalkan job fair massal yang berisiko overload.
Dapat disimpulkan bahwa job fair yang dipadati ribuan orang bukan sekadar pemandangan musiman yang perlu kita syukuri sebagai indikator semangat kerja masyarakat. Kerumunan tersebut harus dibaca sebagai masalah struktural ketenagakerjaan yang perlu dibenahi secara sistematis.
Selama pemerintah dan dunia usaha belum bersinergi memperbaiki kesenjangan keterampilan, memperluas lapangan kerja formal, serta membangun sistem ketenagakerjaan yang sehat, job fair akan terus menjadi cermin ketimpangan yang menyakitkan. Sudah saatnya kita memandang antrean panjang di job fair bukan sekadar kerumunan, melainkan panggilan untuk pembenahan yang lebih mendasar.
Agaknya hal tersebut yang harus diperhatikan pemerintah agar job fair dapat menjadi sarana para pencari kerja yang mayoritas usia produktif dapat mengekspresikan dirinya. Jika hal ini bisa dilakukan, maka bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan dapat dicapai dengan paripurna.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.





