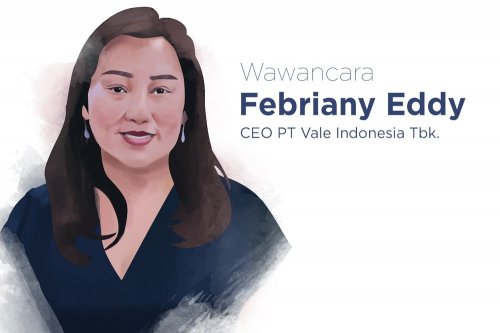Menurut Yusrizki, saat ini teknologi carbon capture sejatinya sudah banyak tersedia meskipun harganya masih sangat mahal. “Kenapa banyak pengusaha masuk ke net zero? Cuma satu alasannya, kami takut. Ada atau tidak ada dukungan pemerintah kami harus tetap jalan sendiri,” katanya.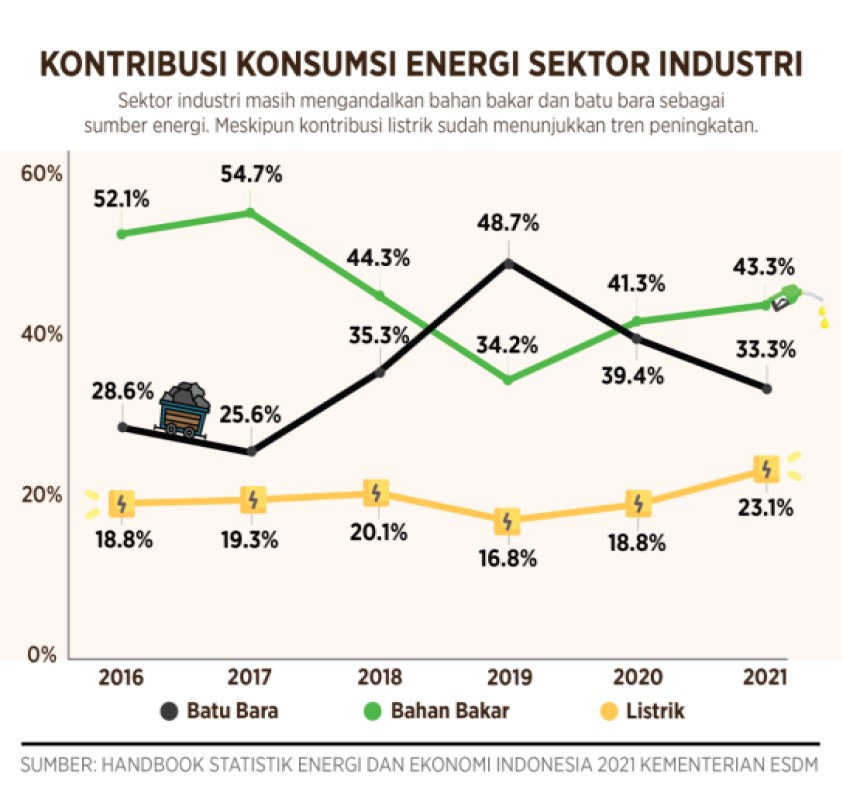
Mekanisme Perdagangan Karbon
Tanggal 7 Oktober 2021 bisa jadi hari yang bersejarah dalam kontes perpajakan di Indonesia. Setelah melalui proses yang berlarut-larut, DPR akhirnya mengetok palu Undang-Undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini memuat banyak perubahan dalam sistem pajak di Indonesia. Salah satu yang signifikan adalah kelahiran pajak karbon.
Saat memberikan pidato pengantar UU HPP pada Oktober tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak karbon akan diterapkan secara bertahap. Nilainya ditetapkan Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen. Sebagai langkah awal, perusahaan pemilik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) jadi sasaran awal objek pajaknya.
Aturan ini semestinya berlaku pada 1 April 2022. Namun hingga memasuki masa tenggat, pemerintah belum menyiapkan aturan turunannya. Kala itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyatakan masih perlu harmonisasi antara UU HPP dan Perpres No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Impelementasi pajak karbon lalu ditunda hingga 1 Juli 2022. Namun memasuki akhir Juni 2022, tanda-tanda penerapan pajak karbon belum juga terlihat. Pemerintah justru kembali menunda implementasinya.
Menkeu Sri Mulyani beralasan penundaan dilakukan karena pemerintah masih melihat dampak yang akan ditimbulkan. Risiko inflasi dan kondisi ekonomi global menjadi alasan kuat. “Kendala teknis sebetulnya tidak ada. Tapi kita mau melihat dampaknya,” katanya.
Pengenaan pajak karbon sejatinya hanya salah satu dari tiga instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Perpres No.98/2021. Selain pajak, beleid ini juga mendorong mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja (result-base payment) dalam skema NEK.
Pembahasan NEK menjadi isu panas dalam upaya mengejar target nol emisi. Riset Indonesia Carbon Trading Handbook yang diterbitkan Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan potensi perdangan karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 8.000 triliun. Ini terutama didukung oleh 125,9 juta hektare hutan tropis dan 3,31 juta hekatre hutan mangrove, serta 7,5 juta hektare lahan gambut. Secara total, hutan Indonesia bisa menyerap lebih dari 100 miliar ton emisi karbon.
Kendati demikian, bukan hal mudah menerapkan perdagangan karbon. Riset KIC merinci beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, tidak semua hutan di Indonesia memenuhi syarat untuk dijadikan proyek karbon. Kedua, metodologi perhitungan kredit karbon masih sangat bervariasi. Ini akhirnya menyulitkan proses penentuan harga karbon.
Pemerintah saat ini telah menentukan harga karbon di kisaran Rp 30.000 per ton CO2. Namun harga ini dianggap terlalu rendah jika dibandingkan dengan patokan harga global sekitar Rp 508.300 per ton CO2.
Tantangan Pendanaan Perdagangan Karbon
Membangun ekosistem perdagangan karbon menjadi krusial sebab butuh ongkos besar untuk mengejar target net zero emission. Hitung-hitungan Kementerian Keuangan menyebutkan Indonesia setidaknya membutuhkan dana hingga Rp 3.799 triliun. Sebagai gambaran, angka ini lebih besar dari APBN 2023 yang ditetapkan senilai Rp 3.041,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap tahun Indonesia sebetulnya membutuhkan anggaran Rp 266 triliun untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, realitanya, APBN hanya menyanggupi sekitar Rp 89,6 triliun per tahun untuk mengatasi persoalan ini.
Lantas, dari mana Indonesia bisa menutupi kekurangan dana sebanyak ini? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Namun ada beberapa skenario yang sedang diupayakan. Salah satunya adalah kerangka energy transition mechanism (ETM), skema pembiayaan campuran untuk mendanai transisi energi yang diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB).
Kerangka ETM pertama kali diperkenalkan di sela-sela COP 26 di Glasgow, awal November silam. ETM dibentuk untuk mengumpulkan dana dari perusahaan swasta, pemerintah, lembaga multilateral, filantropi, dan investor jangka panjang. Salah satu kontributor awalnya adalah pemerintah Jepang yang berkomitmen membenamkan US$ 25 juta dalam skema ini.
Kala itu, Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyebut Indonesia dan Filipina akan menjadi dua negara awal yang memulai proyek percontohan ETM. Lembaga multilateral ini berambisi mengumpulkan miliaran dolar AS yang akan dipakai untuk dua proyek; pensiun dini PLTU dan investasi di energi bersih.
“ETM berpotensi menjadi model penurunan karbon terbesar di dunia,” kata Asakawa.
Asakawa menargetkan sekitar tujuh PLTU di kedua negara akan dipensiunkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Ia meyakini jika sukses diimplementasikan proyek ETM bisa mempensiunkan setengah dari PLTU di Indonesia dan Filipina hanya dalam waktu 10-15 tahun saja. Ini setara dengan memangkas 200 juta ton emisi karbon setiap tahunnya.
Bagi Indonesia, ini seperti durian runtuh. Sudah sejak lama PLTU dianggap sebagai salah satu polutan karbon paling signifikan. Namun, menutup operasional pembangkit batu bara sebelum waktunya akan membutuhkan dana besar.
“ETM adalah proyek ambisius yang akan memperbarui infrastruktur energi Indonesia dan mengakselerasi transisi energi menuju target net zero emission secara adil dan lebih terjangkau,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Setelah meneken komitmen bersama pada November 2021, pemerintah meluncurkan ETM pada Juli 2022. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan skema ini akan dikustomisasi sesuai konteks lokal dan regulasi. Di Indonesia, pendanaan akan melibatakan PT Sarana Multi Infrastruktur, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), SDG Indonesia One (SIO), serta sejumlah lembaga bilateral dan multilateral, juga filantropi.
Dalam perhelatan G20 Summit November mendatang, ETM akan menjadi salah satu prioritas Presidensi Indonesia bersama dengan isu transformasi digital dan arsitektur kesehatan global.
“Tugas yang masih tersisa adalah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mendukung percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan,” kata Febrio.
Menanti Dukungan Regulasi Netralitas Karbon
Regulasi memang masih menjadi hambatan dalam mengejar target netralitas karbon. Lalu, salah satu langkah yang signifikan adalah Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang Percepatan EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Setelah melalui proses panjang, Presiden Joko Widodo menerbitkan beleid ini pada Jumat (16/9/2022).
Melalui aturan ini, Presiden melarang pembangunan PLTU baru di Indonesia. Pun demikian, bukan berarti pembangunan PLTU akan benar-benar dihentikan. Setidaknya ada dua jenis PLTU yang masih diperbolehkan. Pertama, PLTU yang sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan PLTU tertentu yang masuk persyaratan.
Ayat 4 Pasal 3 Perpres menyebut PLTU baru masih boleh dibangun asalkan terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), berkomitmen menurunkan emisi hingga 35% sejak PLTU dibangun, dan PLTU harus beroperasi paling lama hingga 2050.
Menurut Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana, setidaknya ada dua regulasi lagi yang diperlukan untuk mendukung netralitas karbon. Pertama, peraturan pemerintah terkait konservasi energi. Indonesia sebetulnya sudah memiliki beleid ini. Namun Dadan menilai aturan konservasi energi perlu direvisi agar lebih efisien. Selain itu, PP ini akan mengatur keberadaaan manajer energi yang bertugas melaporkan penghematan sumber daya energi.
Regulasi lain yang tidak kalah signifikan adalah Rancangan Undang-Undang tentang inisiatif DPR. Dadan menuturkan pihaknya telah merinci Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang jumlahnya mencapai 600. “Semangatnya begitu,” kata Dadan.
Bagi sektor swasta, transformasi menuju netralitas karbon kini sudah menjadi keharusan. Menurut Ketua Kadin Net Zero Hub Muhammad Yusrizki, ada atau tidak ada insentif dari pemerintah, industri tetap akan membuat insiatifnya sendiri. Pun begitu masih ada sejumlah lubang dalam regulasi yang perlu ditambal pemerintah.
Salah satunya adalah penentuan cap atau batas maksimal emisi yang diperbolehkan di tiap-tiap sektor industri. Yusrizki menegaskan cap ini akan berbeda-beda di setiap sektor. Di sinilah pemerintah harus berperan dengan segera menentukan cap karbon. Sebab, cap akan menjadi tulang punggung dalam mekanisme perdagangan karbon yang didorong pemerintah.
“Sampai saat ini saya belum tahu ada carbon cap,” kata Yusrizki.