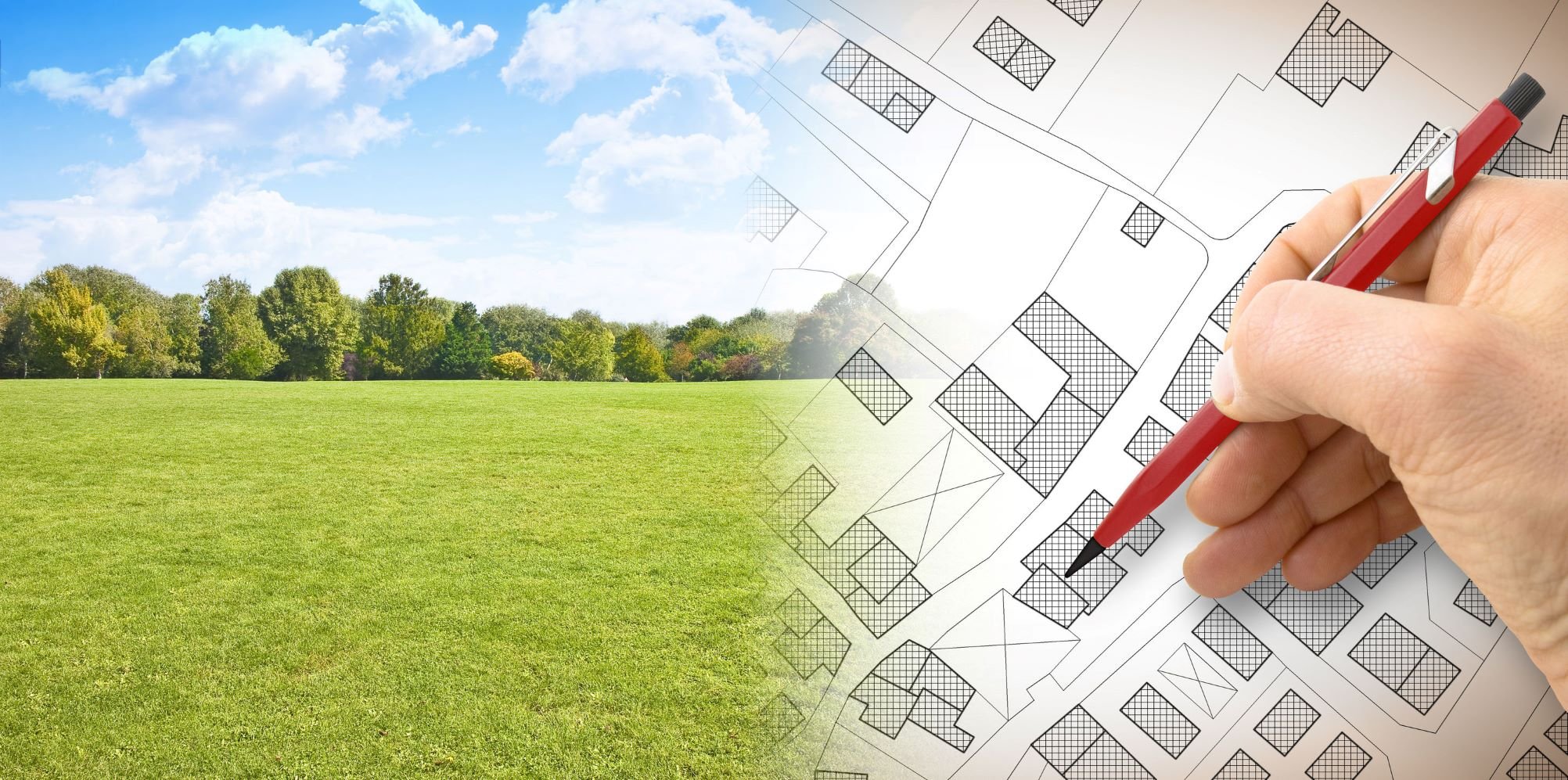Sejak pagi ratusan petani berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Hari ini merupakan Hari Tani Nasional. Kedatangan mereka, salah satunya, untuk menentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan.
Rancangan undang-undang itu tak jauh beda dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak pasal kontroversial dan tak luput dari kritik.
Tapi nasib RUU Pertanahan masih lebih baik ketimbang undang-undang komisi antirasuah. Pembahasannya dialihkan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode mendatang.
Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyampaikan hal itu kemarin. "Sikap pemerintah sangat memperhatikan suara masyarakat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9).
Keputusan itu dibuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan DPR. RUU Pertanahan lolos dalam pembahasan rapat paripurna DPR hari ini.
Namun, para petani tak serta-merta percaya dengan ucapan itu. Mereka tetap datang untuk menunjukkan sikap. “Sekarang ditunda. Bisa saja November disahkan,” kata orator dari atas mobil komando di depan Silang Monas seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebelumnya berpendapat RUU Pertanahan yang ada sekarang bukanlah rancangan aturan yang sesuai dengan agenda reforma agraria. Justru, RUU itu tidak berpihak kepada rakyat, petani, juga masyarakat adat.
"RUU Pertanahan mengatur cara negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan dan setiap warga negara Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika di Jakarta pada akhir pekan lalu.
Prinsip reforma agraria adalah keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Nah, RUU Pertanahan tidak memiliki prinsip menyelesaikan konflik, sumber kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, dan pertimbangan ekologis. “Penyimpangan konstitusi dan UUPA terdapat hampir di seluruh bab dan pasal RUU itu,” ucap Dewi.
(Baca: Serikat Petani Demonstrasi di DPR Tolak Lima Undang-undang Bermasalah)
Persoalan kedua, RUU itu mencantumkan ketentuan pemerintah dapat menerbitkan hak pengelolaan (HPL) tanah berbasis hak menguasai negara. Pemerintah jadi memiliki hak untuk menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 42-45. Menurut Dewi, pasal-pasal ini dapat menimbulkan kekacauan. Apalagi, sebenarnya aturan serupa dengan konsep domein verklaring di zaman kolonial sudah dihapus di UUPA.
Yang ketiga, pasal 25 RUU Pertanahan mengubah perpanjangan hak guna usaha (HGU) dari 35 tahun menjadi bisa diperpanjang hingga dua kali sehingga total mencapai 90 tahun. Padahal, UUPA menyebutkan perpanjangan HGU hanya bisa dilakukan sekali.
Hal lain yang jadi persoalan adalah dalam pasal 79-81 RUU Pertanahan terkait sistem pengadilan pertanahan. Dewi menilai pembentukan pengadilan pertanahan tak bisa menyelesaikan konflik agraria struktural yang selama ini terjadi.
Justru, pembentukan pengadilan pertanahan dapat semakin melemahkan posisi petani, masyarakat miskin dan masyarakat adat atas tanah mereka. Alasannya, melalui pengadilan pertanahan yang akan diutamakan adalah masalah legalitas.
Padahal, banyak tanah petani, masyarakat miskin, dan masyarakat adat diukur bukan berdasarkan legalitas, melainkan prinsip keadilan sosial, pemulihan, hak, dan historis penempatan tanah secara turun-temurun.
(Baca: Darmin Klaim Demonstrasi Mahasiswa Tak Akan Berimbas ke Pasar Keuangan)