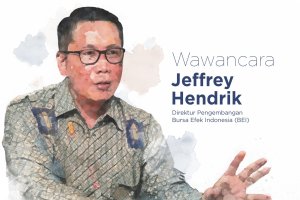Kami Tidak Ingin Moratorium PLTS Seperti Vietnam
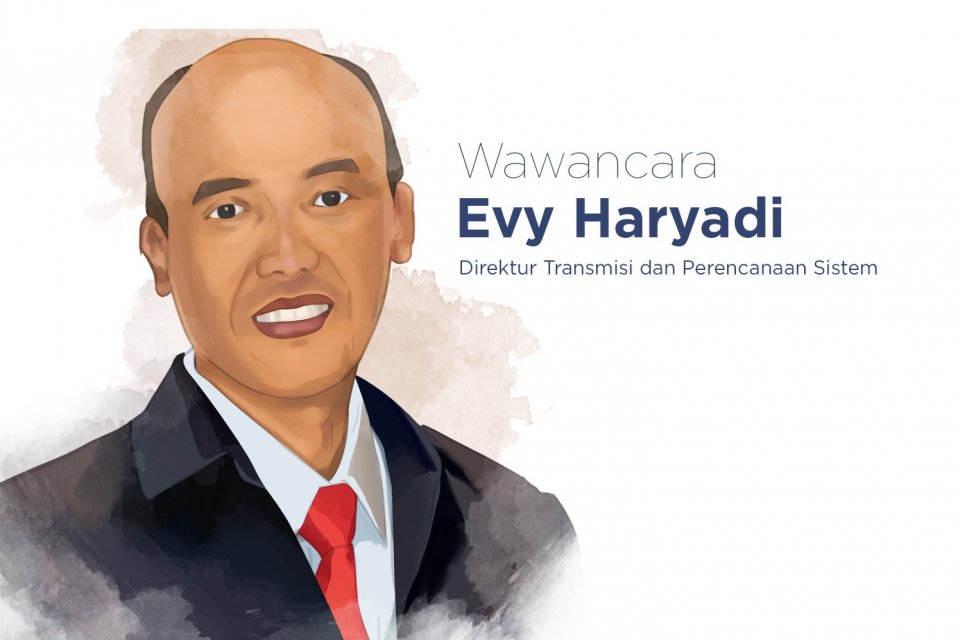
Langkah transisi energi untuk membantu bumi dari efek negatif pemanasan global terus bergema. Satu di antaranya dengan mempercepat pengembangan sumber listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT), seperti pembangkit tenaga surya atap atau PLTS Atap.
Sejumlah kalangan menilai Vietnam masuk jajaran terdepan negara yang mengembangkan pembangkit listrik di EBT. Pada tahun lalu, pembangkit berbahan batu bara di sana tinggal 39 % dari total produksi listrik Vietnam yang mencapai sekitar 80 giga watt.
Selebihnya, hidro pembangkit air menyumbang 36 %. Lalu, sumber baru yang mencakup solar farm, PLTS Atap, energi angin, dan hidro mini berkontribusi 14 %. Adapun turbin gas menghasilkan 11 % listrik.
Angka-angka tersebut memang terbilang besar dibandingkan laju di Indonesia. Hingga akhir 2022, EBT dalam bauran energi nasional baru mencapai 14,11 %. Sebesar 67 % pembangkit masih berbahan bakar batu bara yang menghasilkan emisi besar.
Pemerintah Negeri Naga Biru itu memang sedang giat mengembangkan pembangkit EBT. Di PLTS, misalnya, mereka memberikan aneka insenstif fiskal. Melalui skema feed ini tariff, Vietnam Electricity (EVN), perusahaan seterum negara itu, juga diperintahkan untuk membeli listrik dari pembangkit-pembangkit solar swasta, termasuk surya atap atau roof top, dengan harga tinggi.
Namun, kebijakan tersebut berdampak pada suplai listrik yang berlebih. “EVN kelebihan pasokan yang persis sama dengan PLN di Jawa-Bali,” kata Evy Haryadi, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT Perusahaan Listrik Negara saat wawancara dengan Katadata bersama Majalah Tempo dan Kompas.com beberapa waktu lalu.
Awal tahun ini, direksi dan komisaris PLN sudah dua kali menyambangi Vietnam. Mereka bertukar pengalaman dengan EVN mengenai pengembangan EBT, terutama solar farm dan PLTS Atap.
Banyak pihak menilai transisi energi di Vietnam cukup maju dan layak dicontoh termasuk oleh Indonesia. Bagaimana setelah mengunjungi dan melihat perkembangan di Vietnam?
Tujuan dua kunjungan PLN ke Vietnam, Pak Dirut dan saya, untuk mencari fakta yang riil. Ternyaat, EVN mengalami kelebihan pasokan yang persis sama dengan PLN di Jawa-Bali.
Mereka melakukan inisiatif bauran energi hanya berdasarkan PDP, plan of development plant, atau RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) di kita, dengan insentif feed in tariff tanpa melihat dampak yang muncul. Mereka menyadari setelah secara korporasi ada masalah, apalagi tidak punya buffer seperti PLN yang disubsidi oleh pemerintah.
Yang sangat mengejutkan, di triwulan satu 2023, pertumbuhan permintaan listrik mereka minus. Tarif listrik rata-rata di Vietnam delapan sen. Mereka membeli feed in tariff 9,2 sen untuk pembangkit angin dan 9,8 sen untuk pembangkit solar, jadi membeli lebih mahal. Satu-satunya dukungan pemerintah yaitu kenaikan tarif, yang tiga tahun ini sudah tidak mereka dapatkan.
Sehingga mereka melakukan langkah-langkah independen korporasi. Pertama, kebijakan ekspor listrik ke EVN tidak dibayar lagi. Lalu sudah ada draf PDP 8. Di situ, mereka menyetop selama transisi ini tidak membangun pembangkit solar. PV rooftop juga dibatasi.
Dengan situasi Vietnam seperti itu, apa yang bisa jadi pelajaran bagi Indonesia?
Dulu, ini ingin ditiru oleh pemerintah kita dengan feed in di Perpres, dengan net meterring di PV rooftop. Bahkan, kita lebih agresif lagi. Kalau pemerintah Vietnam hanya menerima ekspor, kita malah memberikan storage-nya.
Kalau pemerintah memaksa PLN untuk menerima storage, artinya pelanggan benar-benar tidak butuh baterai. Pelanggan itu sudah menumpang di infrastruktur PLN tanpa bayar sama sekali. Kalau EVN hanya kehilangan revenue-nya di siang, malam masih beli dari EVN. Itu pun mereka sudah bleeding.
Menurut PLN, semestinya seperti apa kebijakan mengenai pembangkit surya atau atap?
Kami menganggap kebijakan PV rooftop ini tidak fair. Kami minta untuk diubah. Alhamdulillah sudah mau ada revisi. Di revisi ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam bahwa mereka tidak membayar ekspor. Kalau memakai listrik untuk sendiri ya silakan, tapi jangan mengekspor kelebihannya ke PLN.
Sebab ketika meng-ekspor akan menimbulkan berbagai masalah secara power system. Kalau transmisi tidak cukup, beban tidak bisa diserap secara lokal, ya harus dikirim ke tempat lain. Ketika dikirim ke tempat lain itu tergantung kondisi transmisinya.
Jadi cukup kompleks dalam menerapkan PLTS ketika dimasukkan dalam jaringan listrik PLN?
Energi matahari itu probalility. EVN memang membuat weekly forcest, tapi akan setepat apa dengan yang dia buat. Sekarang mataharinya tinggi, tiba-tiba hilang. Dapat dibayangkan tingkat kerumitannya secara teknikal.
Kedua, banyak infrastruktur yang harus disiapkan: control center harus siap memprediksi dengan baik. Ini hal yang baru buat orang operasional. Butuh pelatihan, butuh tools. Dan itu pasti butuh investasi tambahan.
Sehingga transisi energi ini butuh sangat bijaksana. Kita tidak ingin mengulangi yang terjadi pada 2019 ada padam total di Jawa Bali. Kalau kita belum ada kemampuan dan infrastruktur untuk meramalkan renewaable supply dengan tepat, itu bisa menimbulkan ketidaksiapan.
Misalnya, kita meramalkan matahari akan sangat banyak. Karena sangat percaya diri, kita tidak menyiapkan batu bara, gas, atau BBM. Ketika dia tiba-tiba hilang, kita tidak punya energi primer buat pengganti. Itu yang dinamakan balancing cost, ada harga yang harus disiapkan untuk suatu utility.
Di PLN, berdasarkan apa prioritas penggunaan sumber listrik saat ini?
Ada yang harus berjalan. Pertama, run of river. Ini hampir sama dengan matahari dan angin. Run of river itu tidak punya waduk, hanya disodet sedikit di sungai. Ada atau ada tidak ada hujan, pembangkitnya tetap beroperasi. Seperti angin.
Kedua kontrak gas, mau pakai atau tidak, ya, tetap bayar. Kami selalu habiskan karena sudah kontrak. Hanya, kemudian kami review setiap tahun, bisa ada yang digeser untuk tahun depan. Harus punya fleksibilitas, itu ada di dalam kontrak. Misalnya, semua perusahaan tambang batu baru mau ekspor. Atau tiba-tiba tambang kebanjiran. Kami harus bikin kontingensi. Air di waduk juga ada forecest-nya, tapi tiba-tiba kemarau.
Apa negara-negara lain juga menghadapi hal yang sama dalam EBT ini? Ada contoh negara yang bisa menjadi benchmark?
Semua pasti akan menghadapi masalah yang sama. Mereka akan improve sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Misalnya, hanya untuk forecasting renewable solar and wind farm, Vietnam butuh empat tools. Pertama dari pembangkit, kedua data dari dua vendor internasional. Lalu in house forecast search machine, learning AI.
Lalu pengukuran di pembangkit, misal iradiasi matahari. Begitu juga untuk yang roof top. Itu baru data, butuh interpretasi. Perlu tools untuk mengubah data menjadi informasi dan menjadi keputusan. Kalau kita tidak siap, lalu ada pertumbuhan dengan cepat, bahaya black out seperti di 2019 bisa terjadi.
Sudah seperti apa perisapan membangun tools tadi?
Kami dalam upgrading control center yang di Gandul. Mulai tender tahun ini. Tambahannya untuk forcasting suplai. Saat ini yang ada forcasting permintaan, misal cuaca panas maka pemakaian AC akan meningkat, atau ada sepak bola banyak orang menonton televisi.
Kami punya jadwal pemeliharaan, itu harus kami atur. Ada hal di mana pemeliharaan numpuk karena saat itu beban tidak dibutuhkan. Ada juga saat pemeliharaan kami kosongkan ketika beban sedang tinggi-tingginya.
Apa akan ada moratorium untuk pembangunan PLTS Atap di Permen yang baru?
Kalau sampai moratorium itu signal yang jelek. Moratorium kan sudah kuratif, tindakan untuk perbaikan. Nanti bisa dianggap kami tidak friendly terhadap renewable energy.
Kami ingin kebijakannya win-win, tetap memberikan insentif bagi dunia usaha bisa maju bersama. Kami tidak ingin seperti Vietnam sampai moratorium.
PLN juga sebenarnya punya proyek pengembangan EBT?
Kami sudah menghitung, berapa yang bisa dialokasikan. Kenapa RUPTL kemarin lama, karena kami berdebat dengan Kementerian ESDM terkait dengan besaran renewable yang bisa diterima PLN. Sampai akhirnnya putus 4,7 GW untuk solar, 600 MW untuk wind. Itu sudah hasil kompromi.
Sebelumnya kami meminta tidak setinggi itu. Misal, solar dua koma sekian. Yang 4,7 GW ini tidak termasuk roof top. Walaupun kami minta tetap perlu kuota juga untuk roof top, karena ini terkait dengan backup yang mesti kami siapkan. Ini akan masuk ke RUPTL yang akan datang. Sebelumnya 3,6 giga dalam tiga tahun, nanti bisa dalam lima atau enam tahun.
Jadi untuk mengganti bauran energi yang berkurang dari mana?
Kita akan mengejar transisi energi atau value transisi energi yang just dan affordable? Kembali ke kebijakan pemerintah, mau memaksa untuk memenuhi target 23 % pada 2025, dengan risiko cost yang muncul mesti ditanggung. Atau mau just and affordable. PLN akan mengikuti apapun keputusan pemerintah, kami akan bangun.
Target 23 % itu sebenarnya janji ke internal, dalam negeri. Kami ke internasional itu pada 2030 terkait NDC (Nationally Determined Contribution) yang wajib turun sekian persen. Itu wajib kita lakukan karena terkait kredibilitas.
Bagaimana rencana memperbesar pengurangan emisi di NDC tersebut?
Dari 29 % dinaikkan manjdi 31,89 %. Emisi itu terkait dengan mitigasi penurunan emisi, bukan renewable-nya. Menurunkan emisi itu bermacam-macam. Di PLN seperti early retirement. Atau mengganti dari batu bara ke gas. Emisi gas itu separuh dari batu bara. Lalu, perencanaan pembangkit yang pakai batubara tidak lagi pakai batu bara.
Jadi bagaimana arah transisi energi di Indonesia?
Kami akan menyesuaikan dengan balancing suply and demand. Sehingga transisi energi-nya just and affordable. Kami tidak ingin kondisi seperti Vietnam yang terjadi oversupply, punya 79 GW dengan beban hanya 45 GW. Artinya dia punya hampir 75 % reserve. Berdasarkan pengalaman kami, yang optimum itu 30 %. Jadi Vietnam menyia-nyiakan 45 % cadangan. Dia masih agak mending karena ada ekspor listrik ke Kamboja, ada interkoneksi antarnegara. Kita tidak ada.
Bagaimana dari sisi pengurangan emisinya?
Kami akan masukkan ke dalam RUPTL. Kebijakan yang kami lakukan, pertama, dediselisasi ganti untuk yang eksisting. Penggantinya dua, renewable atau gasifikasi melalui LNG. Kedua mengurangi batubara dengan mengoptimalkan co-firing, yang sudah masuk dalam rencana. Ini membutuhkan keterlibatan dunia usaha yang kami perkirakan 10 sampai 14 juta ton pada 2030.
Proses co-firing, saat ini semua pembangkit PLTU memakai batubara yang ada emisinya. Sebagian, sekitar 10 % nanti di-mix dengan biomassa. Secara hitungan emisi, biomassa termasuk zero emisi karena dianggap seimbang. Ketika hidup menyerap CO2, kalau dibakar maka impas. Jadi kalau 10 % dari PLTU dipasang co-firing berarti emisi PLTU sudah berkurang 10 %.
Lalu masih ada beberapa inisiatif lainnya termasuk pembangkit PLTU yang kami lengkapi dengan peralatan-peralatan untuk efisiensi emisi. Misal PLTU dilengkapi FGD, flue gas desulfurization. Termasuk penggunaan hidrogen dan amoniak untuk co-firing, sedang pilot project. Kalau semua ini masih kurang maka harus early retirment.
Early retirement ini akan masuk sekema Just Energy Transition Partnership/JETP?
NDC itu ada dua. Pertama, unconditionally. Kedua, conditionally. Yang unconditionally saat ini Indonesia menyatakan penurunan 31,89 ton pada 2030. Itu atas biaya sendiri. Yang kedua conditionally 43 %, itu yang diminta JETP di 2030. Untuk itu duitnya mana, perlu pembiayaan dari luar.
JETP memberi syarat tiga hal. Pertama, pengkondisian emisi 43 %. Kedua porsi renewable 34 % yang saat ini di RUPTL 24,8 % di 2030. Ketiga, net zero emission yang direncanakan 2060 harus maju ke 2050. Mereka baru komitmen untuk membiayai inisiatif sampai 2030, untuk 34 % renewable dan penurunan 43 % emisi. Biaya yang dikasih US$ 20 miliar.
Itu tidak cukup. Kami sedang menghitung biayanya. Dan hitungan kami, untuk mempercepat dengan membandingkan proses bisnis seperti biasanya US$ 38 miliar, itu mencapi US$ 114 miliar, tiga kali lebih tinggi dibandingkaan kalau normal.
Bagaimana skema pendanannya?
Khusus untuk pemensiunan dini PLTU, kami ingin menggunakan grant. Untuk renewable development, kami menginginkan green financing yang cost of fund-nya seperti didapat dari market. Kalau tidak bisa sediakan itu, yang jangan mengatur-atur.
Dari market, PLN dapat bunga berapa persen?
Sekitar 5 %. Artinya, rate dari mereka mesti di bawah 5 %. Sampai sekarang mereka masih menawarkan sekitar 5 %, ya sama dengan di market. Lebih baik dapat dari market tanpa persyaratan macam-macam, diaudit ini dan itu.